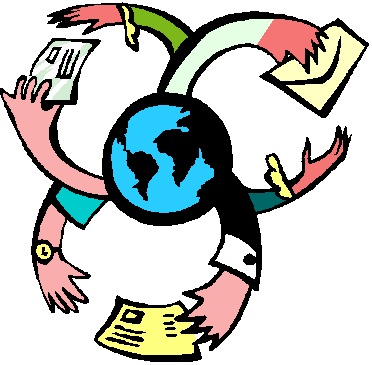Tahun ini masyarakat
Cina kembali bisa merayakan Imlek dengan leluasa. Datanglah ke komunitas
Tionghoa, seperti di kawasan Glodok dan Kota, Jakarta atau daerah
pecinan lainnya. Ada kemeriahan pesta dengan segala asesori berwarna
merah. Ada bagi-bagi ang pao (uang) dan tidak ketinggalan kue
keranjang. Sementara di kelenteng, bau hio bertebaran di tengah
atraksi barong sai dan liong. Inilah kado dari Presiden
Megawati yang telah menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional sejak
2002. Sebelumnya, Abdurrahman Wahid lebih dulu memberikan kado istimewa:
Keppres No.6/2000. Keppres ini bukan hanya membebaskan atraksi
barongsai dalam berbagai upacara, melainkan juga mencabut Inpres
No.14/1967. Inpres No.14/1967 yang dikeluarkan Soeharto ini melarang
segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat secara terbuka.
Namun, apa yang terjadi
sebenarnya baru simbolik dan pada wilayah permukaan. Pasalnya, belenggu
diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa--masyarakat minoritas, tapi
menguasai ekonomi nasional--belum dihapuskan sepenuhnya. Buktinya,
masyarakat Cina tetap memperoleh perlakuan-perlakuan "khusus" yang
bertentangan dengan HAM, khususnya berkaitan dengan catatan sipil.
Konghucu belum
diakui sebagai agama
Meskipun Imlek sudah
ditetapkan sebagai hari libur nasional, Konghucu--sebagai agama
mayoritas warga Tionghoa--belum diakui sebagai agama di Indonesi. Hal
ini dikeluhkan oleh Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu (Matakin)
Budi S. Tanuwibowo. Ia mengakui bahwa hingga saat ini pemeluk agama
Konghucu masih mendapat perlakukan diskriminatif.
Usai pertemuan antara
Panitia Tahun Baru Imlek dengan Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz
(28/01), Budi menyatakan bahwa masih ada kendala-kendala teknis di
lapangan yang mengganggu hak-hak sipil pemeluk Konghucu. Pasalnya,
pemerintah belum mengakui Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia.
Buntutnya, penganut Konghucu sering kesulitan untuk sekadar menulis
agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya. "Kami sulit mencantumkan agama
di KTP. Jadi selama ini agama kami (di KTP) dikosongkan atau diisi
dengan agama lain. Bila ingin menikah tidak bisa di catatan sipil,"
cetus Budi. Padahal, menurutnya, jumlah penganut Konghucu di Indonesia
kurang lebih sekitar 1,5 juta hingga 2 juta. Tampaknya, ketidak-jelasan
posisi Konghucu ini semula berpangkal pada Surat Edaran (SE) Mendagri
No.477/75054 tahun 1978. SE Mendagri ini memberikan petunjuk bahwa untuk
pengisian kolom agama pada KTP, hanya ada lima agama resmi di Indonesia.
"Petugas sering beralasan di komputer cuma tersedia kolom untuk lima
agama," tandas Wahyu Efendy dari Gerakan Perjuangan Anti-Diskriminasi (GANDI).
Padahal, SE Mendagri
ini telah dicabut dengan SE Mendagri No.477/805 tahun 2002. Meskipun
pedoman hanya lima agama tidak berlaku lagi, pada prakteknya birokrat
punya alasan untuk tidak menjalankan surat edaran yang baru. Misalnya,
karena belum ada petunjuk pelaksanaannya (juklak). "Ketidakjelasan
aturan" ini akhirnya menelan korban. Misalnya, kasus pencatatan
pernikahan Konghucu pada pasangan Charles-Suryawati dari Surabaya pada
2001. Akte pernikahan pasangan ini sampai saat ini tidak diberikan oleh
Kantor Catatan Sipil (KCS) karena terbentur masalah "Konghucu bukan
agama resmi negara".
SKBRI jadi momok
Peraturan yang paling
menjadi momok bagi kelompok peranakan Tionghoa adalah Surat Bukti
Kewarganegaraan Republik Indonesia alias SBKRI. Menteri Kehakiman dan
HAM Yusril Ihza Mahendra sebenarnya sudah menegaskan, Departemen
Kehakiman dan HAM tidak akan lagi mengeluarkan SBKRI. Bahkan, Yusril
mengemukakan bahwa bukti kewarganegaraan itu cukup kartu tanda penduduk
(KTP) dan akte kelahiran.
Sesuai dengan UU No.
62/1958 tentang Kewarganegaraan RI, SBKRI diperlukan, tapi bersifat
fakultatif bagi yang memerlukanya. Padahal, keefektifan SKBRI telah
dicabut melalui Keppres No.56 Tahun 1996. B.J. Habibie pun telah
mengeluarkan Inpres No.4 Tahun 1999 yang menghapuskan SBKRI dan izin
pelajaran Bahasa Mandarin. Menurut Keppres itu, bukti kewarganegaraan
seseorang cukup dibuktikan dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP),
kartu keluarga (KK), atau akta kelahiran. Sayangnya, Inpres tersebut
selama ini tidak dilaksanakan. Buktinya, berbagai instansi tetap
mensyaratkan SBKRI, seperti KCS, kelurahan, dan kantor imigrasi. Boleh
jadi, urusan SBKRI jadi alot karena menyangkut duit. Maklum, pengurusan
SBKRI tergolong mahal, sehingga bisa jadi 'obyekan' yang lumayan. Rosita
Noer dari Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) dalam suatu diskusi
mengungkapkan SBKRI mengusik rasa keadilan dan menyuburkan korupsi terus
menerus.
SBKRI memang membuka
peluang gemuk untuk korupsi, karena banyaknya mereka yang mengurus SKBRI.
"Dalam memo surat biasanya dinyatakan akan dijawab pada kesempatan
pertama. Tapi kesempatan pertama itu bisa sampai lima belas tahun," kata
Rosita. Kalau urusan mau cepat, ya UUD...Ujung-Ujungnya Duit. Makin gede
duitnya, urusan makin cepat rampung. Wahyu Efendy berpendapat bahwa
selain tidak efisien, masalah SKBRI menimbulkan diskriminasietnis. "Karena,
prosesnya diskriminatif dan berbau rasis," cetusnya kepada
hukumonline.
Ketidakadilan negara
Molornya pengururusan
SKBRI pernah dikeluhkan Hendrawan, pebulutangkis andalan nasional.
Menjelang persiapan ke Piala Thomas di Ghuangzou, China, pada Mei 2002,
juara dunia tunggal putra tahun 2000 itu masih memikirkan pengurusan
kewarganegaraan yang telah terkatung-katung sejak November 2001. Ia juga
mengungkapkan bahwa SBKRI kakak kandungnya yang sudah 20 tahun ditunggu
sampai kini belum selesai. Ironis, Hendrawan yang ikut jadi pahlawan
untuk merebut kembali Piala Thomas ke bumi pertiwi--malah belum diakui
sebagai warga negara Indonesia, karena dia keturunan Cina! Setelah
Presiden Megawati turun tangan langsung, barulah Hendrawan dan istrinya
memperoleh SBKRI. Ketidakadilan yang dialami Hendrawan juga dialami oleh
putra bangsa--pebulutangkis yang telah mengharumkan nama negara di
pentas dunia--seperti Tong Sin Fu, Tan Joe Hock, Ivana Lie, dan Halim
karena mereka keturunan Cina. Apalagi, terhadap peranakan Tionghoa yang
tidak memiliki prestasi apa-apa.
Selain soal SBKRI,
warga Tionghoa banyak menghadapi masalah ketika berurusan dengan KCS.
Mestinya tidak ada pembedaan antara WNI dan WNA," kata Wahyu. Bahkan
dalam urusan pendidikan pun, menurut Wahyu, peranakan Tionghoa
diperlakukan sebagai orang asing. Belum lagi syarat Surat Pelaporan
Kewarganegaraan RI (K1) bagi warga Tionghoa di Jakarta. "Instruksi
gubernur samar-samar. Biayanya malah membengkak seenaknya sendiri," kata
Eddy Sadeli dari Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat Tionghoa
di Indonesia kepada hukumonline. Namun, menurut Eddy masalah yang
segera dituntaskan adalah ketidakjelasan nasib sekitar 60.000 warga
Tionghoa yang tidak memiliki kewarganegaraan. "Mereka tinggal sudah
puluhan tahun dan beranak pinak di sini, seperti di kawasan Kemayoran,
Jakarta, tapi tidak memiliki kewarganegaraan," kata Edy.
Warga peranakan
Tionghoa itu adalah korban perjanjian bilateral RI-RRC berdasar
Peraturan Presiden No.10/1959. Mereka tidak tidak terangkut ke "tanah
leluhurnya", tapi tidak juga diberi kewarganegaran Indonesia. Mereka
yang masih jadi korban diskriminasi rasial ini pada hari ini masih bisa
mengucap "Gong Xi Fa Cai" sambil berharap ada kejelasan status
kewarganegaraannya. (Rep)
Source:
HukumOnline.com